Hartabuta :
Rabu, 9-6-2021
Versi Tidak Nyungsang Malik :
Leluhur IKS :
A. Walisongo Al Azmatkhan
Versi "https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_Songo"
Wali Songo
Wali Songo (bahasa Jawa: ꦮꦭꦶꦱꦔ; Wali Sɔngɔ) adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata Wali adalah "orang yang dipercaya" atau "orang yang ditugaskan" sedangkan kata Songo dalam (bahasa Jawa: Sɔngɔ) berarti nomor sembilan. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai "Sembilan Wali".
Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa, konteks ini berarti "terhormat".[1]
Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka berketurunan ningrat. (Lihat bagian "Gaya dan Gelar" Kesultanan Yogyakarta untuk penjelasan tentang istilah bangsawan Jawa.)
Makam (pundhen) para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya.[2] Dalam tradisi Jawa makam memiliki istilah pundhen.
Arti Wali Songo
Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang sembilan, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah sembilan, atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata songo / sanga berasal dari kata tsana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat.
Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) pada tahun 1404 Masehi (808 Hijriah).[3] Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok-tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan.
Konsep Wali Songo atau Wali Sembilan dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi sembilan tingkat kewalian. Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibnu Araby atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat al-Makkiyah memaparkan tentang sembilan tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Kesembilan tingkat kewalian itu: 1) Wali Aqthab atau Wali Quthub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2) Wali Aimmah, yaitu pembantu Wali Aqthab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3) Wali Autad, yaitu wali penjaga empat penjuru mata angin . 4) Wali Abdal, yaitu wali penjaga tujuh musim. 5) Wali Nuqaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6) Wali Nujaba, yang setiap masa berjumlah delapan orang. 7) Wali Hawariyyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8) Wali Rajabiyyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. 9) Wali Khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam.[4]
Nama para Wali Songo
Dari nama para Wali Songo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal, yaitu:
|
|
|
Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)
Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandhes, atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan Dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam Ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume (jilid). Dalam Catatan itu tertulis: As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin As-Sayyid Alwi Ammil Faqih bin As-Sayyid Muhammad Shahib Mirbath bin As-Sayyid Ali Khali’ Qasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidhi bin Al-Imam Ja’far Shadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra/Ali bin Abi Thalib, binti Nabi Muhammad Rasulullah
Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarqandy.[5] Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya Kakek Bantal.
Maulana Malik Ibrahim memiliki, 3 isteri bernama:
1. Siti Fathimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israil (Raja Champa Dinasti Azmatkhan 1), memiliki 2 anak, bernama: Maulana Moqfaroh dan Syarifah Sarah
2. Siti Maryam binti Syaikh Subakir, memiliki 4 anak, yaitu: Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad
3. Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmaraqandi, memiliki 2 anak yaitu: Abbas dan Yusuf.
Selanjutnya Sharifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Sayyid Fadhal Ali Murtadha [Sunan Santri/ Raden Santri] dan melahirkan dua putera yaitu Haji Utsman (Sunan Manyuran) dan Utsman Haji (Sunan Ngudung). Selanjutnya Sayyid Utsman Haji (Sunan Ngudung) berputera Sayyid Ja’far Shadiq [Sunan Kudus].
Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat, yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi masjid Jami' Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.
Sunan Ampel (Raden Rahmat)
Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad, menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Champa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Champa Terakhir Dari Dinasti Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin Sayyid Alwi Ammil Faqih bin Sayyid Muhammad Shahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali’ Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidhi bin Imam Ja’far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri adipati Tuban bernama Arya Teja dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo, berputera: Sunan Bonang,Siti Syari’ah,Sunan Derajat,Sunan Sedayu,Siti Muthmainnah dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputera: Dewi Murtasiyah,Asyiqah,Raden Husamuddin (Sunan Lamongan,Raden Zainal Abidin (Sunan Demak),Pangeran Tumapel dan Raden Faqih (Sunan Ampel 2. Makam Sunan Ampel teletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya.
Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam (1977), Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama dua bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada raja muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak mengatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Ario Abdillah.
Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel (1938) menjelaskan bahwa pada waktu Kerajaan Champa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 M, yakni pada tahun jatuhnya Champa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit mencegah Raden Rahmat kembali ke Champa karena Champa sudah rusak akibat kalah perang dengan Kerajaan Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik, tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Champa, sehingga dua bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik, kemudian dinikahkan dengan perempuan setempat.[6]
Sunan Bonang (Makhdum Ibrahim)
Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk Wijil dan tembang Tombo Ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Het Boek van Bonang atau Buku Bonang. Menurut G.W.J. Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur.
Sunan Drajat
Sunan Drajat adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari sunan drajat adalah masih munat. masih munat nantinya terkenal dengan nama sunan drajat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Qasim. Sunan drajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Drajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Drajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Musium Daerah Sunan Drajat, Lamongan. Sunan Drajat diperkirakan wafat pada 1522.
Sunan Kudus
Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus bin Sunan Ngudung bin Fadhal Ali Murtadha bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammil Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja’far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain binti Sayyidah Fathimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, Mursyid Thariqah dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Mesjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550.
Sunan Giri
Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik; yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia timur, bahkan sampai ke kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik.
Sunan Kalijaga
Sunan Kalijaga adalah putra adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur (Syekh Subakir). Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri.
Sunan Muria (Raden Umar Said)
Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari isterinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishaq. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus.
Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)
Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten.
Tokoh pendahulu Wali Songo
Syekh Jumadil Qubro
Syekh Jumadil Qubro adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubra / Husain Jamaluddin al akbar bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Azmatkhan bin Alwi Ammil Faqih bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja’far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Syekh Jumadil Qubro adalah putra Husain Jamaluddin dari isterinya yang bernama Puteri Selindung Bulan (Putri Saadong II/ Putri Kelantan Tua). Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babad dan cerita rakyat sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa.
Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang, Trowulan, atau di desa Turgo (dekat Pelawangan), Yogyakarta. Belum diketahui yang mana yang betul-betul merupakan kuburnya.[7]
Syekh Datuk Kahfi
Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Rara Santang (Syarifah Muda'im), yaitu putera dan puteri dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi), raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), Pangeran Pasarean, dan raja-raja Kesultanan Cirebon lainnya.
Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Magribi, Pangeran Makhdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kuwu Cirebon (Pangeran Cakrabuana), dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggrahan Amparan Jati, dibawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua muri-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muidnya:
“Wahai murid-murid ku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat islamiyah itu?”.
Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tabligh di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang, dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah dewan Wali Songo.
Asal usul Wali Songo
Teori keturunan Hadramaut
Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand (Asia Tengah), Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tampat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubaligh daripada merupakan asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al Baqir, dalam bukunya Thariqah Menuju Kebahagiaan, mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut (Yaman):
- L.W.C van den Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada 1884–1886, dalam bukunya Le Hadhramout et les colonies arabes dans l'archipel Indien (1886)[8] mengatakan:
- ”Adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam (ke Indonesia) adalah dari orang-orang Sayyid Syarif. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut (yang bukan golongan Sayyid Syarif), tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka (kaum Sayyid Syarif) adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam (Nabi Muhammad SAW).”
- van den Berg juga menulis dalam buku yang sama (hal 192-204):
- ”Pada abad ke-15, di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya, yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang kuat itu. Orang-orang Arab bercampul-gaul dengan penduduk, dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan. Rupanya pembesar-pembesar Hindu di kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab, oleh karena sebagian besar mereka berketurunan pendiri Islam (Nabi Muhammad SAW). Orang-orang Arab Hadramawt (Hadramaut) membawa kepada orang-orang Hindu pikiran baru yang diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab, mengikuti jejak nenek moyangnya."
- Pernyataan van den Berg spesifik menyebut abad ke-15, yang merupakan abad spesifik kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di pulau Jawa. Abad ke-15 ini jauh lebih awal dari abad ke-18 yang merupakan saat kedatangan gelombang berikutnya, yaitu kaum Hadramaut yang bermarga Assegaf, Al Habsyi, Al Hadad, Alaydrus, Alatas, Al Jufri, Syihab, Syahab dan banyak marga Hadramaut lainnya.
- Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermadzhab Syafi’i, sama seperti mayoritas di Srilangka, pesisir India Barat (Gujarat dan Malabar), Malaysia dan Indonesia. Bandingkan dengan umat Islam di Uzbekistan dan seluruh Asia Tengah, Pakistan dan India pedalaman (non-pesisir) yang sebagian besar bermadzhab Hanafi.
- Kesamaan dalam pengamalan madzhab Syafi'i bercorak tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait; seperti mengadakan Maulid, membaca Diba & Barzanji, beragam Shalawat Nabi, doa Nur Nubuwwah dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di Hadramaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Srilangka, Sulu & Mindanao, Malaysia dan Indonesia. Kitab fiqh Syafi’i Fathul Muin yang populer di Indonesia dikarang oleh Zainuddin Al Malabary dari Malabar, isinya memasukkan pendapat-pendapat baik kaum Fuqaha maupun kaum Sufi. Hal tersebut mengindikasikan kesamaan sumber yaitu Hadramaut, karena Hadramaut adalah sumber pertama dalam sejarah Islam yang menggabungkan fiqh Syafi'i dengan pengamalan tasawuf dan pengutamaan Ahlul Bait.
- Pada abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Wali Songo seperti Raden Patah dan Pati Unus sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut juga merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14, yaitu cucu keluarga besar Azhamat Khan (atau Abdullah Khan) bin Abdul Malik bin Alwi, seorang anak dari Muhammad Shahib Mirbath ulama besar Hadramaut abad ke-13. Keluarga besar ini terkenal sebagai mubaligh musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara, dan mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar, seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nuralam Akbar dan banyak lainnya.
Teori keturunan Cina (Hui)
Sejarawan Slamet Muljana mengundang kontroversi dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa (1968), dengan menyatakan bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Muslim.[9] Pendapat tersebut mengundang reaksi keras masyarakat yang berpendapat bahwa Wali Songo adalah keturunan Arab-Indonesia. Pemerintah Orde Baru sempat melarang terbitnya buku tersebut.[butuh rujukan]
Referensi-referensi yang menyatakan dugaan bahwa Wali Songo berasal dari atau keturunan Tionghoa sampai saat ini masih merupakan hal yang kontroversial. Referensi yang dimaksud hanya dapat diuji melalui sumber akademik yang berasal dari Slamet Muljana, yang merujuk kepada tulisan Mangaraja Onggang Parlindungan, yang kemudian merujuk kepada seseorang yang bernama Resident Poortman. Namun, Resident Poortman hingga sekarang belum bisa diketahui identitasnya serta kredibilitasnya sebagai sejarawan, misalnya bila dibandingkan dengan Snouck Hurgronje dan L.W.C van den Berg. Sejarawan Belanda masa kini yang banyak mengkaji sejarah Islam di Indonesia yaitu Martin van Bruinessen, bahkan tak pernah sekalipun menyebut nama Poortman dalam buku-bukunya yang diakui sangat detail dan banyak dijadikan referensi.
Salah satu ulasan atas tulisan H.J. de Graaf, Th.G.Th. Pigeaud, M.C. Ricklefs berjudul Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries adalah yang ditulis oleh Russell Jones. Di sana, ia meragukan pula tentang keberadaan seorang Poortman. Bila orang itu ada dan bukan bernama lain, seharusnya dapat dengan mudah dibuktikan mengingat ceritanya yang cukup lengkap dalam tulisan Parlindungan.[10]
Sumber tertulis tentang Wali Songo
- Terdapat beberapa sumber tertulis masyarakat Jawa tentang Wali Songo, antara lain Serat Walisanga karya Ranggawarsita pada abad ke-19, Kitab Wali Songo karya Sunan Dalem (Sunan Giri II) yang merupakan anak dari Sunan Giri, dan juga diceritakan cukup banyak dalam Babad Tanah Jawi.
- Mantan Mufti Johor Sayyid `Alwî b. Tâhir b. `Abdallâh al-Haddâd (meninggal tahun 1962) juga meninggalkan tulisan yang berjudul Sejarah perkembangan Islam di Timur Jauh (Jakarta: Al-Maktab ad-Daimi, 1957). Ia menukil keterangan di antaranya dari Haji `Ali bin Khairuddin, dalam karyanya Ketrangan kedatangan bungsu (sic!) Arab ke tanah Jawi sangking Hadramaut.
- Dalam penulisan sejarah para keturunan Bani Alawi seperti al-Jawahir al-Saniyyah oleh Sayyid Ali bin Abu Bakar Sakran, 'Umdat al-Talib oleh al-Dawudi, dan Syams al-Zahirah oleh Sayyid Abdul Rahman Al-Masyhur; juga terdapat pembahasan mengenai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang dan Sunan Gresik.
Referensi
- Russell Jones, review on Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th Centuries written by H. J. de Graaf; Th. G. Th. Pigeaud; M. C. Ricklefs, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 50, No. 2. (1987), hlm. 423-424.
Lihat pula
- Alawiyyin
- Azmatkhan
- Mazhab Syafi'i
- Suku Arab-Indonesia
- Syekh Muhammad Shahib Mirbath
- Sunan Bayat
- Ki Ageng Pandan Arang
- Syekh Siti Jenar
- Resident Poortman
- Syekh Shohibul Faroji Azmatkhan Ba'alawi Al-Husaini
- Majelis Dakwah Walisongo
- Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar
Pranala luar
- (Inggris) Najmuddin al-Kubra, Jumadil Kubra and Jamaluddin al-Akbar: Traces of Kubrawiyya influence in early Indonesian Islam Online publication of Martin van Bruinessen, by Universiteit Utrecht
- (Indonesia) Syekh Hasanuddin: Pendiri Pesantren Pertama di Jawa Barat Republika Online: Jumat, 28 April 2006
B. Kerajaan Mataram ILAAM
C. Kerajaan Pajang
D. Kerajaan Demak Bintoro
E. Kerajaan Mojopahit
https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit
Majapahit
Kemaharajaan Majapahit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293–1527 | |||||||||
![Peta wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan Nagarakertagama[1]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Majapahit_Empire_id.svg/250px-Majapahit_Empire_id.svg.png) Peta wilayah kekuasaan Majapahit berdasarkan Nagarakertagama[1] | |||||||||
| Status | Kemaharajaan | ||||||||
| Ibu kota | Mojokerto (masa Raden Wijaya) Trowulan (masa Jayanagara) Kediri (masa Girishawardhana) | ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Jawa Kuno (utama), Kawi (alternatif), Sanskerta | ||||||||
| Agama | Siwa-Buddha (Hindu dan Buddha), Kejawen, Animisme | ||||||||
| Pemerintahan | Monarki | ||||||||
| Sri Maharaja | |||||||||
• 1293-1309 | Raden Wijaya | ||||||||
• 1309-1328 | Jayanagara | ||||||||
• 1328-1350 | Tribhuwana Wijayatunggadewi | ||||||||
• 1350-1389 | Hayam Wuruk | ||||||||
• 1389-1429 | Wikramawardhana | ||||||||
• 1429-1447 | Suhita | ||||||||
• 1447-1451 | Kertawijaya | ||||||||
• 1451-1453 | Rajasawardhana | ||||||||
• 1456-1466 | Girishawardhana | ||||||||
• 1466-1474 | Suraprabhawa | ||||||||
• 1474-1498 | Girindrawarddhana/ Brawijaya | ||||||||
| Sejarah | |||||||||
• Penobatan Raden Wijaya | 10 November 1293 | ||||||||
• Invasi Kesultanan Demak | 1527 | ||||||||
| Mata uang | Koin emas, koin perak, koin kepeng, koin gobog | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang bagian dari | |||||||||
|
Bagian dari seri mengenai |
|---|
| Sejarah Indonesia |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Garis waktu |
|
|
| Bagian dari seri artikel mengenai |
| Sejarah Malaysia |
|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 M. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389.
Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia.[2] Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina (Kepulauan Sulu, Manila (Saludung)), Sulawesi, Papua, dan lainnya.[3]
Historiografi
Sejarah mengenai kemaharajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi.[4][5] Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Pararaton ('Kitab Raja-raja') dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama dalam bahasa Jawa Kuno.[6] Pararaton menceritakan Ken Arok (pendiri Kerajaan Singhasari) namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakertagama merupakan puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin Nagarakretagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam Warisan Ingatan Dunia (Memory of the World Programme) oleh UNESCO.[7] Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa Kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain.[8]
Beberapa sarjana seperti C.C. Berg menganggap sebagian naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan.[9] Namun, banyak pula sarjana yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang cukup meyakinkan.[5] Tahun 2010 sekelompok pengusaha Jepang dipimpin Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit of Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takajo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerjasama Majapahit dan Kerajaan Jepang melawan Kerajaan China (Mongol) dalam perang di Samudera Pasifik.[10] Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore John N. Miksic jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra dan Singapura bahkan Thailand yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung dan seni.[11] Bahkan ada perguruan silat bernama Kali Majapahit yang populer di Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari Kemaharajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia dan Selatan Thailand.[12]
Sejarah
Berdirinya Majapahit
Sebelum berdirinya Majapahit, Singhasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa Dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Meng Chi[13] ke Singhasari yang menuntut upeti. Kertanagara, penguasa kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya.[13][14] Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293.
Ketika itu, Jayakatwang, adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Aria Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan, Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang.[15] Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati.[15] Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa "pahit" dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut karena mereka berada di negeri asing.[16][17] Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu enam bulan lagi di pulau yang asing.
Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang tepercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Ra Jaran Waha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, dan Ra Tati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Pararaton.[18] Slamet Muljana menduga bahwa mahapatih Halayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang tepercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir (Kuti), Halayudha ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati.[17] Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309.
Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kala Gemet, yang berarti "penjahat lemah". Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya, akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijayatunggadewi untuk menjadi ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih, pada saat pelantikannya Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk.
Kejayaan Majapahit
Hayam Wuruk, juga disebut Rajasanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada (1313-1364), Majapahit menguasai lebih banyak wilayah.
Menurut Kakawin Nagarakretagama pupuh XIII-XV, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatra, semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian kepulauan Filipina.[19] Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit.
Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja.[21] Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok.[2][21]
Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Citraresmi (Pitaloka), putri Kerajaan Sunda sebagai permaisurinya.[22] Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam.[23] Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk redam melakukan "bela pati", bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya.[24] Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahiyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagarakretagama.
Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatra ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali, di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras.[25]
Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang.[2]
Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit tampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini.
Surutnya Majapahit
Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan takhta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan takhta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatra dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, dimana semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh Dinasti Ming.[26]
Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas takhta.[5] Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, semetara Wirabhumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang.
Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut Dinasti Ming yang dipimpin oleh laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel; maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa.[27]
Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabhumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bhre Pamotan menjadi raja dengan gelar Rajasawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 M. Terjadi jeda waktu tiga tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan takhta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik takhta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singhawikramawardhana. Pada 1468 pangeran Kertabhumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai raja Majapahit.[8]
Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara.[28] Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatra. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu per satu mulai melepaskan diri.
Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di pulau Sumatra hanya tinggal Indragiri, Jambi dan Palembang, sebagaimana ditulis pada catatan Yingyai Shenglan ciptaan Ma Huan, salah satu penerjemah laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Syah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatra.
Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bhre Kertabumi, Singhawikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha (bekas ibu kota Kerajaan Kediri) dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabhumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Budha atas kebijakan Bhre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak.
Waktu berakhirnya Kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 (tahun 1400 saka,[Catatan 1] berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan) hingga tahun 1527.[29]
Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candrasengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah “sirna hilanglah kemakmuran bumi”. Namun yang sebenarnya digambarkan oleh candrasengkala tersebut adalah gugurnya Bhre Kertabumi, raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana.[30] Raden Patah yang saat itu adalah adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sunan Ngudung, tetapi mengalami kekalahan dan bahkan Sunan Ngudung meninggal di tangan Raden Kusen adik Raden Patah yang memihak Ranawijaya hingga para dewan wali menyarankan Raden Fatah untuk meneruskan pembangunan masjid Demak.
Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiyu dan Petak, Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabhumi [30] dan memindahkan ibu kota ke Daha (Kediri). Peristiwa ini memicu perang antara Ranawijaya dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabhumi. Pada masa ini, Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit[31] yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman pulau Jawa. Sebenarnya perang ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara melakukan kudeta ke Girindrawardhana dan mengakui kekuasan Demak bahkan menikahi anak termuda Raden Patah, tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Prabu Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit[29] dan ke Malaka. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabhumi.
Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit.[32] Demak di bawah pemerintahan Raden (kemudian menjadi Sultan) Patah (Fatah), diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut Babad Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri China.
Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis (Tome Pires), dan Italia (Pigafetta) mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 M.[30]
Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru.
Militer dan persenjataan
Pada zaman Majapahit terjadi perkembangan, pelestarian, dan penyebaran teknik pembuatan keris. Teknik pembuatan keris mengalami penghalusan dan pemilihan bahan menjadi semakin selektif. Keris pra-Majapahit dikenal berat namun semenjak masa ini dan seterusnya, bilah keris yang ringan tetapi kuat menjadi petunjuk kualitas sebuah keris. Penggunaan keris sebagai tanda kebesaran kalangan aristokrat juga berkembang pada masa ini dan meluas ke berbagai penjuru Nusantara, terutama di bagian barat.
Berdasarkan buku Sejarah Yuan, prajurit pada masa Majapahit awal didominasi oleh infanteri ringan. Pada saat serbuan Mongol ke Jawa (1293), tentara Jawa dideskripsikan sebagai prajurit yang dimobilisasi sementara dari petani dan beberapa prajurit bangsawan. Para bangsawan berbaris di garis depan, dan pasukan belakang yang besar berformasi T terbalik. "Tentara petani" Jawa berpakaian setengah telanjang dan ditutupi dengan kain katun di bagian pinggangnya (sarung). Sebagian besar senjata adalah busur dan panah, tombak bambu, dan pedang pendek. Kaum aristokrat sangat dipengaruhi oleh budaya India, biasanya dipersenjatai dengan pedang dan tombak, dan berpakaian putih.[33][34]
- Cetbang berjenis meriam tangan, ditemukan di sungai Brantas, Jombang.
- Sebuah cetbang berlaras ganda di atas pedati meriam (gun carriage), dengan garpu putar, sekitar tahun 1522. Mulut meriam berbentuk Nāga Jawa.
Selain keris, berkembang pula teknik pembuatan dan penggunaan tombak dan meriam kapal sederhana yang disebut Cetbang. Majapahit di bawah Mahapatih (perdana menteri) Gajah Mada memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut.[35] Cetbang awal (disebut cetbang bergaya Timur) bentuknya mirip meriam dan meriam tangan Cina. Cetbang bergaya Timur kebanyakan dibuat dari bahan perunggu dan merupakan meriam isian depan. Ia menembakkan proyektil berupa panah, namun peluru bulat dan proyektil co-viative[Catatan 2] juga dapat digunakan. Panah ini dapat berujung pejal tanpa peledak, maupun disertai bahan peledak dan pembakar di belakang ujungnya. Di bagian dekat belakang, terdapat kamar atau bilik bakar, yang merujuk kepada bagian yang menggelembung dekat belakang meriam, dimana mesiu ditempatkan. Cetbang ini dipasang pada dudukan tetap, ataupun sebagai meriam tangan yang diletakkan di ujung galah. Ada bagian mirip tabung di bagian belakang meriam. Pada cetbang jenis meriam tangan, tabung ini digunakan sebagai tempat untuk menancapkan galah.[36]
Karena dekatnya hubungan maritim Nusantara dengan wilayah India Barat, setelah tahun 1460 jenis senjata bubuk mesiu baru masuk ke Nusantara melalui perantara orang Arab. Senjata ini sepertinya adalah meriam dan bedil tradisi Turki Usmani, misalnya prangi, yang merupakan meriam putar isian belakang.[36] Ia menghasilkan cetbang jenis baru, disebut "cetbang bergaya Barat". Ia dapat dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar, yang kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut Penjajap (Portugis: Pangajaua atau Pangajava), dan juga Lancaran. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal. Pada zaman ini, bahkan sampai abad ke 17, prajurit angkatan laut Nusantara bertempur di panggung yang biasa disebut Balai (lihat gambar kapal). Ditembakan pada kumpulan prajurit dengan peluru scattershot (peluru sebar atau peluru gotri, dapat berupa grapeshot, case shot, atau paku dan batu), cetbang sangat efektif untuk pertempuran jenis ini.[37][38] Saat ini salah satu koleksi Cetbang Majapahit tersebut berada di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika.
Majapahit memiliki pasukan elit yang disebut Bhayangkara. Tugas utama pasukan ini adalah untuk melindung raja dan kaum bangsawan, namun mereka juga dapat diterjunkan ke pertempuran jika diperlukan. Hikayat Banjar mencatat perlengkapan Bhayangkara di istana Majapahit:
... dengan perhiasannya orang berbaju rantai empat puluh serta pedangnya berkopiah taranggos sachlat merah, orang membawa astengger [senapan sundut] empat puluh, orang membawa perisai serta pedangnya empat puluh, orang membawa dadap [perisai rotan] serta sodoknya [senjata mirip tombak dengan mata lebar] sepuluh, orang membawa panah serta anaknya sepuluh, yang membawa tombak rampukan bersulam emas empat puluh, yang membawa tameng Bali bertulis air empat puluh.
— Hikayat Banjar. 6.3[39]
Patung dewa memegang sebuah kuiras, dari Nganjuk, Jawa Timur, pada masa sebelumnya (abad ke-10 sampai ke-11).
Menurut catatan China, prajurit yang lebih kaya menggunakan baju pelindung yang disebut kawaca.[Catatan 3] Baju pelindung ini berbentuk seperti tabung panjang dan terbuat dari tembaga yang dicetak. Walaupun begitu, prajurit yang lebih miskin pergi berperang dengan telanjang dada.[40] Jenis baju zirah lain yang digunakan di Jawa era Majapahit adalah waju rante (zirah rantai) dan karambalangan (lapisan logam yang dikenakan di depan dada).[39][41][42] Dalam Kidung Sunda pupuh 2 bait 85 dijelaskan bahwa mantri-mantri (menteri atau perwira) Gajah Mada mengenakan baju besi dalam bentuk zirah rantai atau plastron dengan hiasan emas dan mengenakan pakaian kuning,[43] sedangkan dalam Kidung Sundayana pupuh 1 bait 95 disebutkan bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian.[41][42]
Majapahit juga mengawali penggunaan senjata api di Nusantara. Meskipun pengetahuan membuat senjata berbasis serbuk mesiu di Nusantara sudah dikenal setelah serangan Mongol ke Jawa, dan pendahulu senjata api, yaitu meriam galah (bedil tombak), dicatat digunakan oleh Jawa pada tahun 1413,[37][44] pengetahuan membuat senjata api sejati datang jauh kemudian, setelah pertengahan abad ke-15. Ia dibawa oleh negara-negara Islam di Asia Barat, kemungkinan besar oleh orang Arab. Tahun pengenalan yang tepat tidak diketahui, tetapi dapat dengan aman disimpulkan tidak lebih awal dari tahun 1460.[45] Suatu catatan tentang penggunaan senjata api pada pertempuran melawan pasukan Giri pada sekitar tahun 1500-1506 berbunyi:[46]
"... wadya Majapahit ambedili, dene wadya Giri pada pating jengkelang ora kelar nadhahi tibaning mimis ...""... pasukan Majapahit menembaki (bedil=senjata api), sementara pasukan Giri berguguran karena mereka tidak kuat dihujani peluru (mimis=peluru bulat)..."
- Serat Darmagandhul
Tidak diketahui secara pasti jenis senjata api apa yang digunakan dalam pertempuran ini. Kata "bedhil" dapat merujuk ke beberapa jenis senjata bubuk mesiu yang berbeda. Itu mungkin merujuk pada arquebus Jawa (Zua Wa Chong - 爪哇銃) yang dilaporkan oleh orang China. Arquebus ini memiliki kemiripan dengan arquebus Vietnam pada abad ke-17. Senjata ini sangat panjang, dapat mencapai 2,2 m panjangnya, dan memiliki dudukan bipod yang dapat ditekuk.[47]
Catatan Tome Pires tahun 1513 menyebutkan pasukan tentara Gusti Pati, wakil raja Batara Brawijaya, berjumlah 200.000 orang, 2.000 diantaranya adalah prajurit berkuda dan 4.000 adalah musketir.[48] Duarte Barbosa sekitar tahun 1514 mengatakan bahwa penduduk Jawa sangat ahli dalam membuat artileri dan merupakan penembak artileri yang baik. Mereka membuat banyak meriam 1 pon (cetbang atau rentaka), senapan lontak panjang, spingarde (arquebus), schioppi (meriam tangan), api Yunani, gun (bedil besar atau meriam), dan senjata api atau kembang api lainnya.[49][50] Setiap tempat disana dianggap sangat baik dalam mencetak/mengecor artileri, dan juga dalam ilmu penggunaanya.[49][51]
Kavaleri sejati pertama, unit terorganisir dari penunggang kuda yang kooperatif, mungkin telah muncul di Jawa selama abad ke-12 M.[52] Naskah Jawa kuno kakawin Bhomāntaka menyebutkan kisah kuda Jawa awal dan sejarah menunggang kuda.[53] Naskah tersebut mungkin mencerminkan konflik (secara alegoris) antara kavaleri Jawa yang baru jadi dan infanteri elit mapan yang membentuk inti dari pasukan Jawa sampai abad ke-12.[54] Pada abad ke-14 M, Jawa menjadi peternak kuda yang penting dan pulau ini bahkan terdaftar di antara pemasok kuda ke Cina.[55] Selama masa Majapahit, jumlah kuda dan kualitas kuda keturunan Jawa terus berkembang sehingga pada tahun 1513 masehi Tomé Pires memuji kuda-kuda yang sangat dihiasi dari bangsawan Jawa, dilengkapi dengan sanggurdi bertatahkan emas dan pelana yang dihiasi dengan mewah yang "tidak ditemukan di tempat lain di dunia".[48]
Untuk angkatan laut, armada Majapahit menggunakan djong/jong secara besar-besaran sebagai kekuatan lautnya. Pada puncaknya Majapahit memiliki 5 armada perang. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah total jong yang dimiliki Majapahit, tetapi jumlah terbesar yang pernah digunakan dalam satu ekspedisi adalah berjumlah 400 buah, tepatnya saat Majapahit menyerang Pasai.[56] Setiap kapal berukuran panjang sekitar 70-180 meter, berat sekitar 500-800 ton dan dapat membawa 200-1000 orang. Kapal ini dipersenjatai meriam sepanjang 3 meter, dan banyak cetbang berukuran kecil.[39] Sebuah jong dari tahun 1420 memiliki daya muat 2000 ton dan hampir saja menyeberangi samudera Atlantik.[57] Sebelum tragedi Bubat tahun 1357, raja Sunda dan keluarganya datang di Majapahit setelah berlayar di laut Jawa dalam armada dengan 200 kapal besar dan 2000 kapal yang lebih kecil.[43] Kapal yang dinaiki keluarga kerajaan adalah sebuah jong hibrida Cina-Asia tenggara bertingkat sembilan (Bahasa Jawa kuno: Jong sasanga wagunan ring Tatarnagari tiniru). Kapal hibrida ini mencampurkan teknik China dalam pembuatannya, yaitu menggunakan paku besi selain menggunakan pasak kayu dan juga pembuatan sekat kedap air (watertight bulkhead), dan penambahan kemudi sentral.[58][59] Jenis kapal lain yang digunakan Majapahit adalah malangbang, kelulus, lancaran, penjajap, jongkong, cerucuh, tongkang, dan pelang.[56][60][61] Penggambaran angkatan laut Majapahit di masa modern sering kali menggambarkan kapal-kapal bercadik, namun pada kenyataannya kapal ini berasal dari abad ke-8 yaitu kapal Borobudur, yang digunakan dinasti Sailendra. Penelitian oleh Nugroho menyimpulkan bahwa kapal yang digunakan oleh Majapahit tidak menggunakan cadik, dan menggunakan ukiran Borobudur sebagai dasar rekonstruksi kapal Majapahit adalah salah.[39][62]
Selama era Majapahit penjelajahan orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Ludovico di Varthema (1470-1517), dalam bukunya Itinerario de Ludouico de Varthema Bolognese menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke "negeri jauh di selatan" hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana satu hari hanya berlangsung selama empat jam dan "lebih dingin daripada di bagian dunia mana pun". Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak setidaknya 900 mil laut (1666 km) selatan dari titik paling selatan Tasmania.[63]
Orang Jawa, seperti suku-suku Austronesia lainnya, menggunakan sistem navigasi yang mantap: Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda, dan dengan memakai suatu teknik perbintangan sangat khas yang dinamakan star path navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenali dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala.[64] Pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah digunakan, selain itu kartografi (ilmu pemetaan) telah berkembang. Pada tahun 1293 Raden Wijaya memberikan sebuah peta dan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan, menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa.[65] Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis rhumb, dan garis rute langsung yang dilalui kapal dicatat oleh orang Eropa, sampai-sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an.[63][66]
Ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka (1511), orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa, yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika. Mengenai peta itu, Albuquerque berkata:[67]
"... peta besar seorang mualim Jawa, yang berisi Tanjung Harapan, Portugal dan tanah Brazil, Laut Merah dan Laut Persia, Kepulauan Cengkih, navigasi orang Cina dan Gom, dengan garis rhumb dan rute langsung yang bisa ditempuh oleh kapal, dan dataran gigir (hinterland), dan bagaimana kerajaan berbatasan satu sama lain. Bagiku, Tuan, ini adalah hal terbaik yang pernah saya lihat, dan Yang Mulia akan sangat senang melihatnya memiliki nama-nama dalam tulisan Jawa, tetapi saya punya saya orang Jawa yang bisa membaca dan menulis, saya mengirimkan karya ini kepada Yang Mulia, yang ditelusuri Francisco Rodrigues dari yang lain, di mana Yang Mulia dapat benar-benar melihat di mana orang Cina dan Gore (Jepang) datang, dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Kepulauan Cengkih, dan di mana tambang emas ada, pulau Jawa dan Banda, tindakan seperiodenya, dari siapa pun sezamannya, dan tampaknya sangat mungkin bahwa apa yang dia katakan adalah benar..." - Surat untuk raja Manuel I dari Portugal, April 1512.
Kebudayaan
"Dari semua bangunan, tidak ada tiang yang luput dari ukiran halus dan warna indah" [Dalam lingkungan dikelilingi tembok] "terdapat pendopo anggun beratap ijuk, indah bagai pemandangan dalam lukisan... Kelopak bunga katangga gugur tertiup angin dan bertaburan di atas atap. Atap itu bagaikan rambut gadis yang berhiaskan bunga, menyenangkan hati siapa saja yang memandangnya".
— Gambaran ibu kota Majapahit kutipan dari Nagarakertagama.
Nagarakretagama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra (Maret-April) ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam tiga jenis: keraton termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya; wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja; serta wilayah-wilayah taklukan di kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas.[68]
Ibu kota Majapahit di Trowulan merupakan kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa (pemuja Wisnu) dipeluk oleh penduduk Majapahit, dan raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa, maupun Wisnu. Nagarakertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam, akan tetapi sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana muslim saat itu.[2]
Walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelumnya, arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya.[69] Candi-candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan getah tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemui sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit, antara lain gerbang terbelah candi bentar, gapura paduraksa (kori agung) beratap tinggi, dan pendopo berdasar struktur bata. Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa dan Bali.
".... Raja [Jawa] memiliki bawahan tujuh raja bermahkota. [Dan] pulaunya berpenduduk banyak, merupakan pulau terbaik kedua yang pernah ada.... Raja pulau ini memiliki istana yang luar biasa mengagumkan. Karena sangat besar, tangga dan bagian dalam ruangannya berlapis emas dan perak, bahkan atapnya pun bersepuh emas. Kini Khan Agung dari China beberapa kali berperang melawan raja ini; akan tetapi selalu gagal dan raja ini selalu berhasil mengalahkannya."
— Gambaran Majapahit menurut Mattiussi (Pendeta Odorico da Pordenone).[70][Catatan 4]
Catatan yang berasal dari sumber Italia mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan dari catatan perjalanan Mattiussi, seorang pendeta Ordo Fransiskan dalam bukunya: "Perjalanan Pendeta Odorico da Pordenone". Ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara: Sumatra, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Ia dikirim Paus untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tengah. Pada 1318 ia berangkat dari Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia, terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Srilanka. Lalu menuju kepulauan Nikobar hingga mencapai Sumatra, lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, China, terus mengikuti Jalur Sutra menuju Eropa pada 1330.
Di buku ini ia menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi. Disebutkan raja Jawa menguasai tujuh raja bawahan. Disebutkan juga di pulau ini terdapat banyak cengkih, kemukus, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ia menyebutkan istana raja Jawa sangat mewah dan mengagumkan, penuh bersepuh emas dan perak. Ia juga menyebutkan raja Mongol beberapa kali berusaha menyerang Jawa, tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebutkan di sini tak lain adalah Majapahit yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun 1318-1330 pada masa pemerintahan Jayanegara.
Diplomat Portugis Tome Pires, yang mengunjungi Nusantara pada 1512, mencatat kebudayaan Jawa pada akhir zaman Majapahit. Kisah Pires menceritakan tentang para tuan dan bangsawan di Jawa. Mereka digambarkan sebagai:
... tinggi dan tampan, dengan dekorasi mewah, dan mereka memiliki banyak kuda yang sangat dihiasi. Mereka menggunakan keris, pedang, dan tombak dari berbagai jenis, semuanya bertatahkan emas. Mereka adalah pemburu dan penunggang kuda yang hebat - kuda itu memiliki sanggurdi semua bertatahkan emas dan pelana yang juga bertatahkan, yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Penguasa Jawa begitu mulia dan agung sehingga tidak ada bangsa yang bisa dibandingkan dengan mereka di wilayah yang luas di bagian ini. Kepala mereka dicukur - setengah dicukur - sebagai tanda keindahan, dan mereka selalu mengusap rambut mereka dari dahi ke atas tidak seperti yang dilakukan orang Eropa. Penguasa Jawa dipuja seperti dewa, dengan rasa hormat yang tinggi dan penghormatan yang dalam.
Para bangsawan pergi berburu atau mencari kesenangan dengan gaya yang agung. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka dalam kesenangan, pengiring memiliki begitu banyak tombak dengan gagang emas dan perak, begitu kaya tatahannya, dengan begitu banyak anjing jenis harrier, greyhound dan anjing lainnya; dan mereka memiliki begitu banyak gambar yang dilukis dengan pemandangan dan pemandangan berburu. Pakaian mereka dihiasi dengan emas, keris, pedang, pisau, kelewang mereka semua bertatahkan emas; mereka memiliki sejumlah selir, kuda jennet, gajah, lembu untuk menarik kereta dari kayu yang dicat dan bersepuh emas. Para bangsawan pergi dengan kereta kemenangan, dan jika mereka pergi melalui laut mereka pergi dengan kelulus yang dicat dan dihiasi; ada apartemen indah untuk wanita mereka, tempat lain untuk para bangsawan yang menemaninya.[48]
Kesusasteraan
Pada zaman Majapahit ditulis berbagai kakawin (puisi berbahasa Jawa Kuno), seperti Negarakertagama, prosa, seperti Pararaton, dan juga muncul berbagai cerita kembangan (carangan, spin off) dari epos raya India dalam bentuk kidung (seperti Tantu Panggelaran, Garudeya, dan Sudhamala) maupun cerita lisan yang populer hingga masa kini, seperti lingkaran cerita Panji, kisah Sri Tanjung, dan kisah Bhubuksah dan Gagangaking. Berbagai ukiran batu candi dari masa ini banyak mengabadikan fragmen cerita-cerita tersebut.[71]
Ekonomi
Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan.[21] Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi: keping uang dalam negeri diganti dengan uang "kepeng" yaitu keping uang tembaga impor dari China. Pada November 2008 sekitar 10.388 keping koin China kuno seberat sekitar 40 kilogram digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit.[72] Alasan penggunaan uang logam atau koin asing ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah, akan tetapi kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal.[73]
Tau-I Chi, yang ditulis sekitar 1350 M, menyebutkan tentang kekayaan dan kemakmuran Jawa pada masa itu:
"Ladang-ladang di Jawa kaya dan tanahnya rata dan berair baik, maka dari itu gandum dan beras berlimpah, dua kali lipat di negara lain. Orang-orang tidak mencuri, dan apa yang dijatuhkan di jalan tidak diambil. Pepatah umum: "Jawa yang makmur" berarti negara ini. Pria dan wanita menutup kepala mereka dan mengenakan pakaian panjang."[74]
Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prasasti. Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri (mandala Jawa).[68] Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karier, mulai dari pengrajin emas dan perak, hingga penjual minuman, dan jagal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak zaman sebelumnya, namun proporsi populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit.
Menurut catatan Wang Ta-Yuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung Kakaktua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga.[75] Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321, menyebutkan bahwa istana raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata.[76]
Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama adalah kesuburan lahan di lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur utara mendukung pertanian padi. Pada masa jayanya Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua adalah pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan penting sebagai ekspor-impor serta transit bagi komoditas rempah-rempah dari timur (Maluku). Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit.[68]
Nagarakretagama menyebutkan bahwa kemasyhuran penguasa Wilwatikta telah menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India, Khmer, Siam, dan Tiongkok. Pajak khusus dikenakan pada orang asing terutama yang menetap semi-permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa.[77]
Selama era Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa. Ini dikarenakan perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutamanya jong, untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh.[39] Ma Huan (penerjemah Cheng Ho) yang mengunjungi Jawa pada 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa adalah memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara.[39]
Struktur pemerintahan
Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya.[78] Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi.
Aparat birokrasi
Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu:
Dalam Rakryan Mantri ri Pakira-kiran terdapat seorang pejabat yang terpenting yaitu Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam dewan pertimbangan kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja, yang disebut Bhattara Saptaprabhu.
Pembagian wilayah
Dalam pembentukannya, kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan Singhasari,[17] terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh uparaja yang disebut Paduka Bhattara yang bergelar Bhre atau "Bhatara i". Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan. Biasanya posisi ini hanyalah untuk kerabat dekat raja. Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak, dan mengirimkan upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin.
Selama masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350 s.d. 1389) ada 12 wilayah di Majapahit, yang dikelola oleh kerabat dekat raja. Hierarki dalam pengklasifikasian wilayah di kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut:
- Bhumi: kerajaan, diperintah oleh Raja
- Nagara: diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan)
- Watek: dikelola oleh wiyasa,
- Kuwu: dikelola oleh lurah,
- Wanua: dikelola oleh thani,
- Kabuyutan: dusun kecil atau tempat sakral.
| No | Provinsi | Gelar | Penguasa | Hubungan dengan Raja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahuripan (atau Janggala, sekarang Sidoarjo) | Bhre Kahuripan | Tribhuwanatunggadewi | ibu suri | ||||||||
| 2 | Daha (bekas ibu kota dari Kediri) | Bhre Daha | Rajadewi Maharajasa | bibi sekaligus ibu mertua | ||||||||
| 3 | Tumapel (bekas ibu kota dari Singhasari) | Bhre Tumapel | Kertawardhana | ayah | ||||||||
| 4 | Wengker (sekarang Ponorogo) | Bhre Wengker | Wijayarajasa | paman sekaligus ayah mertua | ||||||||
| 5 | Matahun (sekarang Bojonegoro) | Bhre Matahun | Rajasawardhana | suami dari Putri Lasem, sepupu raja | ||||||||
| 6 | Wirabhumi (Blambangan) | Bhre Wirabhumi | Bhre Wirabhumi[Catatan 5]1 | anak | ||||||||
| 7 | Paguhan | Bhre Paguhan | Singhawardhana | saudara laki-laki ipar | ||||||||
| 8 | Kabalan | Bhre Kabalan | Kusumawardhani[Catatan 6]2 | anak perempuan | ||||||||
| 9 | Pawanuan | Bhre Pawanuan | Surawardhani | keponakan perempuan | ||||||||
| 10 | Lasem (kota pesisir di Jawa Tengah) | Bhre Lasem | Rajasaduhita Indudewi | sepupu | ||||||||
| 11 | Pajang (sekarang Surakarta) | Bhre Pajang | Rajasaduhita Iswari | saudara perempuan | ||||||||
| 12 | Mataram (sekarang Yogyakarta) | Bhre Mataram | Wikramawardhana[Catatan 6]2 | keponakan laki - laki | ||||||||
|
Catatan: | ||||||||||||
Sedangkan dalam Prasasti Waringin Pitu (1447 M) disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan, yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Bhre.[79] Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu:
|
|
Prasasti ini tidak menyebutkan beberapa daerah yang telah diketahui merupakan dibawah kekuasaan Majapahit berdasarkan sumber-sumber luar, seperti Sulalatus Salatin dan buku Suma Oriental ciptaan Tome Pires. Daerah-daerah ini termasuk :
- Indragiri di Sumatra dan Siantan (sekarang Pontianak pada pesisir barat Kalimantan), yang menurut Sulalatus Salatin, diberikan sebagai hadiah pernikahan kepada Kesultanan Malaka atas pernihkahan sultan Mansur Syah dari Malaka dengan putri Majapahit. Sultan Mansur Syah memerintah pada tahun 1459 - 1477, sehingga pada tahun 1447 artinya Indragiri dan Siantan masih dibawah kekuasaan Majapahit.
- Jambi dan Palembang, yang hanya mulai lepas dari genggaman Majapahit ketika diambil-alih oleh Kesultanan Demak[80] pada saat masa perangnya melawan Majapahit yang diperintah Ranawijaya. Perang antara Demak dan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478 - 1498 ketika Ranawijaya membunuh Bhre Kertabhumi dan terusir kembali ke Daha oleh pasukan Demak
- Dan Bali yang merupakan daerah pengungsian terakhir para bangsawan, seniman, pendeta dan penduduk agama Hindu di Jawa ketika Majapahit runtuh oleh Demak.
Saat Majapahit memasuki era kemaharajaan Thalasokrasi saat pemerintahan Gajah Mada, beberapa negara bagian di luar negeri juga termasuk dalam lingkaran pengaruh Majapahit, sebagai hasilnya, konsep teritorial yang lebih besar pun terbentuk:
- Negara Agung, atau Negara Utama, inti kerajaan. Area awal Majapahit atau Majapahit Lama selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan. Yang termasuk area ini adalah ibu kota kerajaan dan wilayah sekitarnya dimana raja secara efektif menjalankan pemerintahannya. Area ini meliputi setengah bagian timur Jawa, dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para Bhre (bangsawan), yang merupakan kerabat dekat raja.
- Mancanegara, area yang melingkupi Negara Agung. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi, area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi, yang kemungkinan membentuk persekutuan atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menempatkan birokrat dan pegawainya di tempat-tempat ini dan mengatur kegiatan perdagangan luar negeri mereka dan mengumpulkan pajak, namun mereka menikmati otonomi internal yang cukup besar. Wilayah Mancanegara termasuk di dalamnya seluruh daerah Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung dan Palembang di Sumatra.
- Nusantara, adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka harus membayar upeti tahunan. Mereka menikmati otonomi yang cukup luas dan kebebasan internal, dan Majapahit tidak merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini; akan tetapi, tantangan apa pun yang terlihat mengancam ketuanan Majapahit atas wilayah itu akan menuai reaksi keras. Termasuk dalam area ini adalah kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya.
Ketiga kategori tersebut masuk ke dalam lingkaran pengaruh Kerajaan Majapahit. Akan tetapi Majapahit juga mengenal lingkup keempat yang didefinisikan sebagai hubungan diplomatik luar negeri.
Hubungan diplomatik
Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dalam menjalin persekutuan. Semboyan Mitreka Satata digunakan oleh Mahapatih Gajah Mada sebagai landasan dalam menjalankan politik luar negeri Majapahit yang bersifat kekerabatan, hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kutipan ini berasal dari Kakawin Nagarakretagama pupuh 15, bait 1.[81] Lengkapnya ialah:
| Jawa Kuno | Alih bahasa |
|---|---|
| nahan / lwir ning deçantara kacaya de çri narapati, tuhn / tang synakayodyapura kimutang darmmanagari, marutma mwang ring rajapura nuniweh sinhanagari, ri campa kambojanyat i yawana mitreka satata | Such is the aspect of the other countries, protected by the Illustrious Prince;
verily, to be sure: Syangkayodhyapura, together with Dharmanagari, Marutma and Rajapura, and Singhanagari too, Campa, Kamboja. Different is Yawana, that is a friend, regul |
| kunong tekang nusa madura tatan ilwing parapuri, ri denyan tungal / mwang yawadarani rakwaikana danu, samudra(1) nangung(2) bhumi(3) kta ça- (98b) ka kalanya karnö, teweknyan dadyapantara sasiki tatwanya tan adoh | Concerning now this island of Madura, this is not at all of the same aspect as the foreign kingdoms,
because of the fact that it has been one with the Yawa-country, so it is said, at that time in the past: "The oceans carry a country" (124 = 202 A.D.), such is their Shaka-year, one hears, their moment to become provided with an interstice; (nevertheless) they are one in essence, not far away (from each other). |
| huwus rabdang dwipantara sumiwi ri çri narapati, padasthity awwat / pahudama wijil anken / pratimasa, sake kotsahan / sang prabhu ri sakhahaywanyan iniwö, bhujanga mwang mantrinutus umahalot / patti satata. | Already the other continents are getting ready to show obedience to the Illustrious Prince,
alike orderly they bring in all kinds of products every ordained season. As an instance of the honoured Prabhu's exertion for all the good that is taken care of by him, ecclesiastical officers and mandarins are sent to fetch the produce regularly. |
Mitreka Satata yang secara harfiah berarti "persaudaraan yang satu dengan dasar persamaan derajat". Mitreka berasal dari kata mitra dan ika (mitra = sahabat; ika = itu) Satata berarti satu tata (sama derajat dan kekal). Hal itu menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit, bukan sebagai bawahan dalam kekuatan Majapahit. Menurut Negarakertagama pupuh 15, bangsa asing adalah Syangkayodhyapura (Ayutthaya di Thailand), Dharmmanagari (Kerajaan Nakhon Si Thammarat), Marutma, Rajapura dan Sinhanagari (kerajaan di Myanmar), Kerajaan Champa, Kamboja (Kamboja), dan Yawana (Annam). Mitreka Satata dapat dianggap sebagai aliansi Majapahit, karena kerajaan asing di luar negeri seperti China dan India tidak termasuk dalam kategori ini meskipun Majapahit telah melakukan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini.
Pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba seperti ini kemudian diidentifikasi oleh sejarahwan modern sebagai "mandala", yaitu kesatuan yang politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif lebih lanjut.[82] Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup mandala Majapahit, yaitu wilayah Mancanegara dan Nusantara, umumnya memiliki pemimpin asli penguasa daerah tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas. Wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit-banyak dipengaruhi Majapahit, tetap menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa terintegrasi lebih lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Pola kekuasaan mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Angkor, serta mandala-mandala tetangga Majapahit yang sezaman; Ayutthaya dan Champa.
Raja-raja Majapahit
Para penguasa Majapahit adalah penerus dari keluarga kerajaan Singhasari, yang dirintis oleh Sri Ranggah Rajasa, pendiri Wangsa Rajasa pada akhir abad ke-13. Berikut adalah daftar penguasa Majapahit. Perhatikan bahwa terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Rajasawardhana (penguasa ke-8) dan Girishawardhana yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok.[8]
| Nama Raja | Gelar | Tahun |
|---|---|---|
| Raden Wijaya | Kertarajasa Jayawardhana | 1293 - 1309 |
| Jayanagara | Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundarapandya Dewa Adhiswara | 1309 - 1328 |
| Tribhuwana Wijayatunggadewi | Sri Tribhuwanottunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani | 1328 - 1350 |
| Hayam Wuruk | Maharaja Sri Rajasanagara | 1350 - 1389 |
| Wikramawardhana | Bhra Hyang Wisesa Aji Wikrama | 1389 - 1429 |
| Suhita | Prabu Stri Suhita | 1429 - 1447 |
| Kertawijaya | Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana | 1447 - 1451 |
| Rajasawardhana | Rajasawardhana Sang Sinagara | 1451 - 1453 |
| Girishawardhana | Girishawardhana Dyah Suryawikrama | 1456 - 1466 |
| Suraprabhawa | Sri Adi Suraprabhawa Singhawikramawardhana Giripati Pasutabhupati Ketubhuta | 1466 - 1474 |
| Girindrawarddhana/Brawijaya | 1474 - 1527 |
Nama Gelar
Girindrawarddhana
Girīndrawarddhana adalah gelar bagi tiga raja Majapahit terakhir. Ketiga raja Majapahit yang menggunakan gelar ini adalah anak-anak dari Rajasawardhana Sang Sinagara (Raja Majapahit ke-8), yaitu : Dyah Wijayakarana, Dyah Wijayakusuma dan Dyah Ranawijaya Gelar ini ditemukan dalam Prasasti Waringinpitu yang bertahun 1369 Saka (1447 M), serta Prasasti Ptak (OJO XCI) dan Prasasti Jiwu (OJO XCII-XCV) yang keduanya bertahun 1408 Saka (1486 M).[84]
Brawijaya
Brawijaya atau Bhra Wijaya atau Prabu Brawijaya adalah gelar yang dianggap melekat pada penguasa Majapahit, khususnya Dyah Ranawijaya dengan gelar "Brawijaya V" yang dianggap penguasa terakhirnya. Sebagai gelar historis, gelar ini diragukan karena sampai saat ini tidak ada sumber dari masa Majapahit yang menyebutkan adanya gelar Brawijaya.
Warisan sejarah
Majapahit telah menjadi sumber inspirasi kejayaan masa lalu bagi bangsa-bangsa Nusantara pada abad-abad berikutnya.
Legitimasi politik
Kesultanan-kesultanan Islam Demak, Pajang, dan Mataram berusaha mendapatkan legitimasi atas kekuasaan mereka melalui hubungan ke Majapahit. Demak menyatakan legitimasi keturunannya melalui Kertabhumi; pendirinya, Raden Patah, menurut babad-babad keraton Demak dinyatakan sebagai anak Kertabhumi dan seorang Putri Cina, yang dikirim ke luar istana sebelum ia melahirkan. Penaklukan Mataram atas Wirasaba tahun 1615 yang dipimpin langsung oleh Sultan Agung sendiri memiliki arti penting karena merupakan lokasi ibu kota Majapahit. Keraton-keraton Jawa Tengah memiliki tradisi dan silsilah yang berusaha membuktikan hubungan para rajanya dengan keluarga kerajaan Majapahit — sering kali dalam bentuk makam leluhur, yang di Jawa merupakan bukti penting — dan legitimasi dianggap meningkat melalui hubungan tersebut. Bali secara khusus mendapat pengaruh besar dari Majapahit, dan masyarakat Bali menganggap diri mereka penerus sejati kebudayaan Majapahit.[69]
Para penggerak nasionalisme Indonesia modern, termasuk mereka yang terlibat Gerakan Kebangkitan Nasional di awal abad ke-20, telah merujuk pada Majapahit, disamping Sriwijaya, sebagai contoh gemilang masa lalu Indonesia. Majapahit kadang dijadikan acuan batas politik negara Republik Indonesia saat ini.[21] Dalam propaganda yang dijalankan tahun 1920-an, Partai Komunis Indonesia menyampaikan visinya tentang masyarakat tanpa kelas sebagai penjelmaan kembali dari Majapahit yang diromantiskan.[85] Sukarno juga mengangkat Majapahit untuk kepentingan persatuan bangsa, sedangkan Orde Baru menggunakannya untuk kepentingan perluasan dan konsolidasi kekuasaan negara.[86] Sebagaimana Majapahit, negara Indonesia modern meliputi wilayah yang luas dan secara politik berpusat di pulau Jawa.[87]
Beberapa simbol dan atribut kenegaraan Indonesia berasal dari elemen-elemen Majapahit. Bendera kebangsaan Indonesia "Sang Merah Putih" atau kadang disebut "Dwiwarna" ("dua warna"), berasal dari warna Panji Kerajaan Majapahit. Demikian pula bendera armada kapal perang TNI Angkatan Laut berupa garis-garis merah dan putih juga berasal dari warna Majapahit. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka Tunggal Ika", dikutip dari "Kakawin Sutasoma" yang ditulis oleh Mpu Tantular, seorang pujangga Majapahit.
Arsitektur
Majapahit memiliki pengaruh yang nyata dan berkelanjutan dalam bidang arsitektur di Indonesia. Penggambaran bentuk paviliun (pendopo) berbagai bangunan di ibu kota Majapahit dalam kitab Negarakretagama telah menjadi inspirasi bagi arsitektur berbagai bangunan keraton di Jawa serta Pura dan kompleks perumahan masyarakat di Bali masa kini. Meskipun bata merah sudah digunakan jauh lebih awal, para arsitek Majapahitlah yang menyempurnakan teknik pembuatan struktur bangunan bata ini.
Beberapa elemen arsitektur kompleks bangunan di Jawa dan Bali diketahui berasal dari masa Majapahit. Misalnya gerbang terbelah candi bentar yang kini cenderung dikaitkan dengan arsitektur Bali, sesungguhnya merupakan pengaruh Majapahit, sebagaimana ditemukan pada Candi Wringin Lawang, salah satu candi bentar tertua di Indonesia. Demikian pula dengan gapura paduraksa (kori agung) beratap tinggi, dan pendopo berlandaskan struktur bata. Pengaruh citarasa estetika dan gaya bangunan Majapahit dapat dilihat pada kompleks Keraton Kasepuhan di Cirebon, Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah, dan Pura Maospait di Bali. Tata letak kompleks bangunan berupa halaman-halaman berpagar bata yang dihubungkan dengan gerbang dan ditengahnya terdapat pendopo, merupakan warisan arsitektur Majapahit yang dapat ditemukan dalam tata letak beberapa kompleks keraton di Jawa serta kompleks puri (istana) dan pura di Bali.
Kesenian modern
Kebesaran kerajaan ini dan berbagai intrik politik yang terjadi pada masa itu menjadi sumber inspirasi tidak henti-hentinya bagi para seniman masa selanjutnya untuk menuangkan kreasinya, terutama di Indonesia. Berikut adalah daftar beberapa karya seni yang berkaitan dengan masa tersebut.
Puisi lama
- Serat Darmagandhul, sebuah kitab yang tidak jelas penulisnya karena menggunakan nama pena Ki Kalamwadi, namun diperkirakan dari masa Kasunanan Surakarta. Kitab ini berkisah tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan keyakinan orang Majapahit dari agama sinkretis "Hindu" ke Islam dan sejumlah ibadah yang perlu dilakukan sebagai umat Islam.
Komik dan strip komik
- Serial "Mahesa Rani" karya Teguh Santosa yang dimuat di Majalah Hai, mengambil latar belakang pada masa keruntuhan Singhasari hingga awal-awal karier Mada (Gajah Mada), adik seperguruan Lubdhaka, seorang rekan Mahesa Rani.
- Komik/Cerita bergambar Imperium Majapahit, karya Jan Mintaraga.
- Komik Majapahit karya R.A. Kosasih
- Strip komik "Panji Koming" karya Dwi Koendoro yang dimuat di surat kabar "Kompas" edisi Minggu, menceritakan kisah sehari-hari seorang warga Majapahit bernama Panji Koming.
- Komik "Dharmaputra Winehsuka", karya Alex Irzaqi, kisah Ra Kuti dan Ra Semi dalam latar peristiwa pemerontakan Nambi 1316 M.
Roman/novel sejarah
- Sandyakalaning Majapahit (1933), roman sejarah dengan setting masa keruntuhan Majapahit, karya Sanusi Pane.
- Pelangi Di langit Singasari (1968 - 1974), roman sejarah dengan setting zaman kerajaan Kediri dan Singasari, karya S. H. Mintardja.
- Bara Di Atas Singgasana, roman sejarah dengan setting zaman kerajaan singasari dan Majapahit, karya S. H. Mintardja
- Kemelut Di Majapahit, roman sejarah dengan setting masa kejayaan Majapahit, karya Asmaraman S. Kho Ping Hoo.
- Zaman Gemilang (1938/1950/2000), roman sejarah yang menceritakan akhir masa Singasari, masa Majapahit, dan berakhir pada intrik seputar terbunuhnya Jayanegara, karya Matu Mona/Hasbullah Parinduri.
- Senopati Pamungkas (1986/2003), cerita silat dengan setting runtuhnya Singhasari dan awal berdirinya Majapahit hingga pemerintahan Jayanagara, karya Arswendo Atmowiloto.
- Arus Balik (1995), sebuah epos pasca kejayaaan Nusantara pada awal abad 16, karya Pramoedya Ananta Toer.
- Dyah Pitaloka - Senja di Langit Majapahit (2005), roman karya Hermawan Aksan tentang Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Kerajaan Sunda yang gugur dalam Peristiwa Bubat.
- Gajah Mada (2005), sebuah roman sejarah berseri yang mengisahkan kehidupan Gajah Mada dengan ambisinya menguasai Nusantara, karya Langit Kresna Hariadi.
- Jung Jawa (2009), sebuah antologi cerita pendek berlatar Nusantara, karya Rendra Fatrisna Kurniawan, diterbitkan Babel Publishing dengan ISBN 978-979-25-3953-0.
Film/sinetron
- Tutur Tinular, suatu adaptasi film karya S. Tidjab dari serial sandiwara radio. Kisah ini berlatar belakang Kerajaan Singhasari pada pemerintahan Kertanegara hingga Majapahit pada pemerintahan Jayanagara.
- Saur Sepuh, suatu adaptasi film karya Niki Kosasih dari serial sandiwara radio yang populer pada kurun dasawarsa pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an. Film ini sebetulnya lebih berfokus pada sejarah Pajajaran namun berkait dengan Majapahit pula.
- Walisanga, sinetron Ramadan tahun 2003 yang berlatar Majapahit pada masa Brawijaya V hingga Kesultanan Demak pada zaman Sultan Trenggana.
- Puteri Gunung Ledang, sebuah film Malaysia tahun 2004, mengangkat cerita berdasarkan legenda Melayu terkenal, Puteri Gunung Ledang. Film ini menceritakan kisah percintaan Gusti Putri Retno Dumilah, seorang putri Majapahit, dengan Hang Tuah, seorang perwira Kesultanan Malaka.
Permainan video
- Civilization V: Brave New World yang terbit pada Juli 2013, terdapat peradaban Indonesia dengan tokoh pemimpinnya Gajah Mada. Meskipun dinamakan peradaban 'Indonesia', namun perdaban ini menggunakan Surya Majapahit sebagai simbolnya. Peradaban ini memiliki bangunan unik yaitu Candi, yang memiliki ikon bergambar Candi bentar di Trowulan, Mojokerto.
- Kemudian pada Civilization VI sebuah DLC memiliki salah satu pemimpin Majapahit, Dyah Gitarja sebagai pemimpin peradaban Indonesia dengan simbolnya berupa Surya Majapahit yang lebih sederhana. Unit unik untuk peradaban ini adalah jong, yang menggantikan frigate.
- Age of Empires II: The Age of Kings ekspansi keempat Rise of Rajas yang terbit pada Desember 2016, menampilkan misi sebagai Gajah Mada, dari awal pendirian Majapahit mengusir tentara Mongolia dan Kediri (Kerajaan Singhasari), menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di kepulauan Nusantara setelah Sumpah Palapa hingga peristiwa Perang Bubat yang mengakhiri karier Gajah Mada sebagai Mahapatih kerajaan Majapahit. Bangunan Candi bentar, Gapura Bajang Ratu serta Candi Kalasan ditampilkan secara visual pada misi Gajah Mada. Gajah Mada juga muncul di Age of Empires II Definitive Edition yang dirilis pada November 2019.
- Bendera Majapahit, Getih-Getah Samudra atau Gula Kelapa, ada dalam Age of Empires III Definitive Edition (rilis Oktober 2020) sebagai bendera untuk Indonesia, sebuah negara revolusioner yang hadir bagi peradaban Belanda. Sebuah unit bernama Cetbang Cannon tersedia untuk Indonesia.
Lihat pula
- Kakawin Nagarakretagama
- Pararaton
- Kidung Sunda
- Brawijaya
- Kerajaan Singhasari
- Sejarah Nusantara
- Gajah Mada
- Museum Pusat Informasi Majapahit
Catatan
- Kusumawardhani (putri raja) menikah dengan Wikramawardhana (keponakan raja), pasangan ini menjadi ahli waris bersama.
Referensi
- "Kerajaan Majapahit". Sejarah Kerajaan. Diakses tanggal 8 August 2021.
Daftar pustaka
- Mulyana, Slamet (2006). Tafsir sejarah nagarakretagama (dalam bahasa Indonesia). PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 122. ISBN 978-979-2552-546.
- Komandoko, Gamal (2009). Gajah
Mada: menangkis ancaman pemberontakan Ra Kuti: kisah ketangguhan
seorang patih Majapahit dalam menjaga keutuhan takhta sang raja (dalam bahasa Indonesia). Penerbit Narasi. hlm. 122. ISBN 978-979-164-145-2 Periksa nilai: checksum
|isbn=(bantuan).
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki media mengenai Majapahit. |
- (Inggris) Memories of Majapahit - memuat sejarah dan keterangan situs-situs peninggalan Majapahit.
- (Indonesia) Diskusi tentang Perseteruan Ming dan Majapahit
- (Indonesia) Terjemahan Naskah Asli Kitab Negarakretagama Karya Mpu Prapanca Diarsipkan 2013-06-15 di Wayback Machine. - Dari situs www.sejarahnasional.org
| Didahului oleh: Singasari |
Kerajaan Hindu-Budha 1292–1527 |
Diteruskan oleh: Demak |
Bahasa lain
F. Kerajaan Singosari Malang
G. Kerajaan Jenggolo/Jenggala Kahuripan
H. Kerajaan Doho/Daha Kediri
I. Kerajaan Kahuripan Masa Prabu Airlangga
J. Kerajaan Medang Kamulan Dyah Empu Sendok
K. Kerajaan Kalingga Ratu Shima
L. Kerajaan Pajajaran
M. Kerajaan Galuh
N. Kerajaan Sunda
O. Kerajaan Hindhu Mataram - Wangza Sanjoyo/Sanjaya
M. Kerajaan Budha Sriwijaya - Wangza Syailendera
P. Kerajaan Tarumanegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarumanagara
Tarumanagara
Tarumanagara | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450–700 | |||||||||||
 Wilayah Tarumanagara | |||||||||||
| Ibu kota | Sundapura (dekat Tugu dan Bekasi) | ||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Sunda, Sanskerta | ||||||||||
| Agama | Hindu, Buddha, Sunda Wiwitan | ||||||||||
| Pemerintahan | Monarki | ||||||||||
| Maharaja | |||||||||||
• 358 – 382 | Jayasingawarman | ||||||||||
• 666-669 | Linggawarman | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
• Didirikan | 450 | ||||||||||
• Runtuh | 700 | ||||||||||
| |||||||||||
| Sekarang bagian dari | |||||||||||
Bagian dari seri mengenai |
|---|
| Sejarah Indonesia |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Garis waktu |
|
|
Tarumanagara atau Kerajaan Taruma (bahasa Sunda: ᮊᮛᮏᮃᮔ᮪ ᮒᮛᮥᮙ, translit. Karajaan Taruma) adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 M.[1] Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu.[2] Kata tarumanagara berasal dari kata taruma dan nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara sedangkan taruma berasal dari kata tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yaitu Ci Tarum. Pada muara Ci Tarum ditemukan percandian yang luas yaitu Percandian Batujaya dan Percandian Cibuaya yang diduga merupakan peradaban peninggalan Kerajaan Taruma.[3][4]
Sumber sejarah
Sumber dalam Negeri
Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu prasasti Ciaruteun, prasasti Pasir Koleangkak, prasasti Kebonkopi, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Cidanghiang. Prasasti menyebutkan nama raja yang berkuasa adalah Purnawarman.[5][6][7]
Prasasti Kebon Kopi (Prasasti Tapak Gajah)
Lokasi prasasti ini di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad XIX oleh N.W. Hoepermans, tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dinamakan prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam sehingga seiring dengan bertambahnya waktu tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca.[8]
Alih aksara:
"-- -- jayavisalasya tarume(ndra)sya ha(st)ina? -- -- (°aira) vatabhasya vibhatidam=padadvaya? ||" yang artinya “Di sini tampak sepasang tapak kaki ... yang seperti (tapak kaki) Airawata, gajah penguasa Taruma (yang) agung dalam ... dan (?) kejayaan”.[8][9]
Prasasti Tugu
Lokasi saat ini Prasasti Tugu di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Punawarman ditemukan pada abad ke-X Masehi tertulis dalam bahasa Sanskerta, aksara Pallawa dalam bentuk sloka dengan metrum anustubh. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat pemerintahan raja Purnawarman, prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun.[10]
Prasasti Tugumenerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Rajadirajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.[11]
Prasasti Cidanghiang (Prasasti Munjul)
Lokasi prasasti ini di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kapubaten Pandeglang. Lokasinya masih insitu, ditemukan di tepi sungai Cidanghiang. Pada prasasti ini tertulis dalam bahasa Sanskerta, dengan aksara Pallawa dan metrum anustubh, tampak keausan dan permukaan yang ditutupi lumut pada permukaan prasasti ini namun tulisan masih dapat dibaca.[12] Isi dari prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap raja Purnawarman. Prasasti ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh Toebagus Roesjan dan diteliti pada tahun 1947.[13]
Alih aksara dari prasasti yaitu:
(1) "vikranto ‘yam vanipateh | prabhuh satyapara[k]ramah" yang berarti "Inilah (tanda) keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia" (2) "narendraddhavajabhutena | srimatah purnnavarmanah" yang berarti "Yang Mulia Purnnawarman, yang menjadi panji sekalian raja-raja”.[12]
Prasasti Ciaruteun
Lokasi Prasasti Ciaruteun di Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor[14] ditemukan di aliran Sungai Ciaruteun, Bogor pada tahun 1863, prasasti ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Prasasti Ciaruteun A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa terdiri atas 4 baris puisi India (irama anustubh) , dan Prasasti Ciaruteun B berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba yang belum diketahui maknanya, Menurut juru kunci Prasasti Ciaruteun, simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah perkasa dan berkuasa.[15][16] Prasasti ini memiliki ukuran 2 meter dengan tinggi 1.5 meter, berbobot 8 ton.[17]
Alih aksara dari prasasti ini yaitu:
Baris pertama: vikkrantasya vanipateh
Baris kedua: srimatah purnnavarmmanah
Baris ketiga: tarumanagarendrasya
Baris keempat: visnor=iva padadvayam ||[18]
Artinya:
“Inilah sepasang (telapak) kaki, yang seperti (telapak kaki) Dewa Wisnu, ialah telapak kaki Yang Mulia Purnnawarman, raja di negara Taruma (Tarumanagara), raja yang gagah berani di dunia”.[18]
Berdasarkan pesan yang terdapat pada Prasasti Ciaruteun kita mengetahui bahwa prasasti ini dibuat pada abad ke-V dan menginformasikan bahwa pada masa lalu terdapat Kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Raja Purnawarmanyang memuja Dewa Wisnu yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan India, terbukti pada nama raja yang berakhiran -warman,[7] dan tapak kaki yang menandakan kuasa pada zamannya.[17][16] Pada tahun 1863, prasasti ini sempat hanyut diterjang banjir sehingga tulisan yang ada menjadi terbalik, kemudian pada 1903 prasasti ini dikembalikan ke tempat semula, dan pada 1981 barulah prasasti ini dilindungi.[17]
Prasasti Muara Cianten
Lokasi Prasasti Muara Cianten di Kampung Muara, Desa Ciaruteun, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. [19] Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh N.W. Hoepermans dan beberapa tokoh lainnya, ukuran Prasasti Muara Cianten sekitar 2,7 x 1.4 x 1.4 meter dengan jenis batu andesit, hingga saat ini isi prasasti ini belum dapat dibawa sebab menggunakan huruf sangkha atau ikal seperti huruf pada Prasasti Pasir Awi dan Ciaruteun B.[20]
Prasasti Jambu (Prasasti Pasir Koleangkak)
Lokasi Prasasti Jambu di Desa Parakanmuncung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, tempat ditemukannya prasasti ini merupakan Perkebunan Karet Sadeng Djamboe pada masa Kolonial Belanda, Prasasti ini ditemukan pada tahun 1854 oleh Jonathan Rigg, diduga dibuat pada abad ke-V. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya, tertulis dalam huruf Pallawa, dengan bahasa Sanskerta dan terdapat pahatan sepasang telapak kaki.[21]
Alih aksara dari prasasti ini yaitu:
śrīmān=dātā kṛtajño narapatir=asamo yah purā [tā]r[ū]māya[ṃ] / nāmnā śrīpūrṇṇavarmmā pracuraripuṡarābhedadyavikhyātavarmmo / tasyedam=pādavimbadbadvayam=arinagarotsāda ne nityadakṣam / bhaktānām yandripāṇām=bhavati sukhakaraṃ śalyabhūtaṃ ripūṇām.[22]
Arti dari aksara ini yaitu:
“Gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin yang tiada taranya – Yang Termashur Sri Purnnawarman – yang sekali waktu (memerintah) di Taruma, dan yang baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya”.[22]
Sumber Berita dari Luar Negeri
Sumber berita lain yang membuktikan berdirinya Kerajaan Tarumanagara berasal dari berita Cina, berupa catatan perjalanan Fa-Hien (penjelajah dari Cina) dalam bentuk buku dengan judul "Fa-Kuo-Chi" menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 M, di Ye-Po-Ti banyak orang Brahmana dan animisme.[23] Pada tahun 414 M Fa-Hien datang ke tanah Jawa untuk membuat catatan sejarah kerajaan To-lo-mo (Kerajaan Tarumanagara), dan singgah di Ye-Po-Ti selama 5 bulan.[24] Selain itu, berita Dinasti Sui menuliskan bahwa pada tahun 528 dan 535, utusan To-lo-mo telah datang dari sebelah selatan. Berita Dinasti Tang menuliskan bahwa pada tahun 666 dan 669 utusan To-lo-mo telah datang. Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Tarumanagara berkembang antara tahun 400-600 M, yang pada saat itu masa kepemimpinan Raja Purnawarman dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh Jawa Barat.[24]
Peninggalan di Masa Tarumanagara
Penginggalan-peninggalan pada masa Kerajaan Tarumanagara berupa 7 prasasti dan artefak lainnya, sebagai berikut:
| Nama situs | Artefak | Keterangan |
|---|---|---|
| Kampung Muara[25] | Menhir (3) |
|
| Batu dakon (2) | ||
| Arca batu tidak berkepala | ||
| Struktur Batu kali | ||
| Kuburan (tua) | ||
| Ciampea[26] | Arca gajah (batu) | Rusak berat |
| Gunung Cibodas[27] | Arca | Terbuat dari batu kapur |
| 3 arca berdiri |
| |
| arca raksasa |
| |
| arca (?) | Fragmen | |
| Arca dewa |
| |
| Arca dwarapala |
| |
| Arca Brahma | Duduk diatas angsa (Wahana Hamsa) dilengkapi padmasana | |
| Arca (berdiri) | Fragmen kaki dan lapik | |
| (Kartikeya?) |
| |
| Arca singa (perunggu) | Mus.Nas.no.771 | |
| Tanjung Barat[27] | Arca Siwa (duduk) perunggu | Mus.Nas.no.514a |
| Tanjungpriok[27] | Arca Durga-Kali Batu granit | Mus.Nas. no.296a |
| Tidak diketahui | Arca Rajaresi[28] | Mus.Nas.no.6363 |
| Cilincing | sejumlah besar pecahan | settlement pattern |
| Buni | perhiasan emas dalam periuk | settlement pattern |
| Tempayan |
| |
| Beliung |
| |
| Logam perunggu |
| |
| Logam besi |
| |
| Gelang kaca |
| |
| Manik-manik batu dan kaca |
| |
| Tulang belulang manusia |
| |
| Sejumlah besar gerabah bentuk wadah |
| |
| Batujaya (Karawang) | Unur (hunyur) sruktur bata | Percandian |
| Segaran I |
| |
| Segaran II |
| |
| Segaran III |
| |
| Segaran IV |
| |
| Segaran V |
| |
| Segaran VI |
| |
| Talagajaya I |
| |
| Talagajaya II |
| |
| Talagajaya III |
| |
| Talagajaya IV |
| |
| Talagajaya V |
| |
| Talagajaya VI |
| |
| Talagajaya VII |
| |
| Cibuaya[29] | Arca Wisnu I |
|
| Arca Wisnu II |
| |
| Arca Wisnu III |
| |
| Lemah Duwur Wadon | Candi I | |
| Lemah Duwur Lanang | Candi II | |
| Pipisan batu |
|
Naskah Wangsakerta
Naskah Wangsakerta menjadi polemik dikalang sejarahwan, sebab naskah-naskah ini diragukan keasliannya sehingga sulit untuk dijadikan patokan sejarah. Sebelumnya, pada tahun 1980-an polemik di majalah, surat kabar, kalangan arkeolog terjadi bahkan sampai diangkat ke percaturan nasional. Penulisan Naskah Wangsakerta berlangsung selama 21 tahun dibawah pimpinan Pangeran Wangsakerta menggunakan kertas daluang dan tinta hitam dan bertahan selama 100 tahun, dapat dikatakan bahwa naskah yang ada di Museum Sri Baduga merupakan naskah salinan. Isi dari naskah ini mendeskripsikan mengenai sejarah pulau-pulau di Nusantara, Pulau jawa dan Sunda. Bahkan uraian sejarah tertulis lengkap muai dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara hingga daftar raja-raja yang memerintah dan tahun pemerintahan tertulis secara rinci. Naskah Wangsakerta terdiri atas 5 karangan dengan judul Carita Parahyangan, Nagarakrebhumi, Pustaka Dwipantaraparwa, Pustaka Pararatwan, I Bhumi Jawadwipa dan Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara. Polemik muncul sebab naskah-naskah ini tergolong modern dan begitu lengkap.[30]
Raja-Raja Tarumanagara
Kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh 12 raja, raja terakhir yaitu Raja Linggawarman pada tahun 669 M. Kerajaan Tarumanagara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Sunda,Tarusbawa lebih menginginkan kerajaannya sediri yaitu Sunda.[31] Namun, hingga hari in belum diketahui secara pasti kapan Kerajaan Tarumanagara berakhir.[32] Sejarahnya, pada tahun 358 M Rajadirajaguru Jayasingawarman mendirikan Tarumanagara, dan pada masa kejayaan Purnawarman sebagai raja ketiga memegang kendali atas 48 kerajaan kecil, wilayah kekuasaannya dimulai dari Salakanagara atau Rajatapura hingga ke Purwalingga.[33]
Hubungan diplomatik Kerajaan Tarumanagara dengan India dan Cina terbentang luas, Raja Purnawarman sempat tinggal selama enam bulan di Yavadi (Jawa) dimana hukum Budha tidak terlalu berkembang namun Brahmana (Hindu) cukup berkembang. Misi diplomatik sampai ke Cina pada tahun 435 M, namun sekitar 650 Kerajaan Tarumanagara dikalahkan oleh Kerajaan Sriwijaya (kerajaan yang didirikan di Sumatra) sehingga mempengaruhi kekuasaannya pada kerajaan-kerajaan kecil yang pernah ditundukkan.[33] Tarumanegara semakin menghilang saat Raja Terakhir Tarumanegara Linggawarman tak memiliki penerus laki - laki.
Dia memiliki dua anak perempuan, yang sulung bernama Manasih dan menjadi istri Tarusbawa. Yang kedua, Subakancana menjadi istri Depuntahyang Srijayanasa, pendiri kerajaan Sriwijaya.[34]
Kehidupan Masa Kerajaan Tarumanagara
Kehidupan politik di masa Kerajaan Tarumanagara diketahui berdasarkan prasasti yang telah ditemukan, berdasarkan prasasti tersebut raja yang berhasil meningkatkan kehidupan rakyat adalah Raja Purnawarman, dalam prasasti tugu yang menuliskan bahwa penggalian kali yang dilakukan membuat kehidupan rakyat makmur dan merasa aman. Selanjutnya kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa, agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi dibuktikan dengan adanya agama Budha dan agama nenek moyang (animisme). Prasasti tugu menuliskan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan 6122 tombak yang dipergunakan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan dengan daerah sekitarnya, hal ini menandakan kehidupan ekonomi rakyatnya tertata rapi. Kehidupan budaya pada masa itu sudah tinggi, ditandai dengan teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang memperlihatkan perkembangan budaya tulis menulis.[24]
Lihat pula
Referensi
- "Fakta Kerajaan Tarumanegara". ilmusaku.com. Diakses tanggal 2020-04-03.
Rujukan
- Richadiana Kartakusuma (1991), Anekaragam Bahasa Prasastidi Jawa Barat Pada Abad Ke-5 Masehi sampai Ke-16 Masehi: Suatu Kajian Tentang Munculnya Bahasa Sunda. Tesis (yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Arkeologi). Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Dinas Purbakala R.I (1964) Laporan Tahunan 1954 Dinas Purbakala Republik Indonesia. Djakarta: Dinas Purbakala
- J.L.Moens (1940)"was Purnawarman van Taruma een Sanjaya?" TBG.81
- J. noorduyn and H.Th.Verstappen (1972), "Purnawarman's River-works near Tugu" BKI 128:298-307
- R.M.Ng.Poerbatharaka (l952), Riwayat Indonesia I. Djakarta: Jajasan Pembangunan
- Soetjipto Wirjosuparto (1963), The Second Wisnu Image of Cibuaya, West Jawa, MISI. I/2: 170-87
- Teguh Asmar (1971), "Preliminary Report on Recent Excavation near the Kenon Kopi Inscription (Kampung Muara)" Manusia Indonesia V(4-6), l971:416-424;
- Teguh Asmar (l971) "The Megalithic Tradition" dalam Haryati Soebadio et.al.(editor) Dynamic of Indonesian History, Amsterdam. 1978:29-40
- W.P.Groeneveldt, Catalogus der Archaeologische Verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia l887
- N.J.Krom "inventaris der Hindoe-Oudheden" ROD 1914-1915.
- Hasan Djafar "Pemukiman-Pemukiman Kuno di Daerah akarta dn Sekitarnya" makalah pada Dskusi Ilmiah Arkeologi VI, Jakarta 11-12 Februari 1988. IAAI Komda Jawa Barat.
- Van der Hoop Catalogus der Prehistorische Verzameling. 1941.
- R.P.Soejono "Indonesia (REgional REport)" Asian Perspectives VI, 1962: 23-24
- I Made Sutayasa (l970) "Gerabah Prasedjarah dari Djawa Barat Utara (kompleks Bun), makalah pada Seminar Sjarah Nasional II
- Jurusan Arrkeologi FSUI (l985/1986), Peninggalan Purbakala di Batujaya (naskah Laporan untuk Proyek Penelitian Purbakala, Jakarta)
- Sundapura
Bacaan selanjutnya
- Ayatrohaedi, 2005, Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah-naskah "Panitia Wangsakerta" Cirebon. Jakarta: Pustaka Jaya. ISBN 979-419-330-5
- Saleh Danasasmita, 2003, Nyukcruk sajarah Pakuan Pajajaran jeung Prabu Siliwangi. Bandung: Kiblat Buku Utama. ISBN
- Yoseph Iskandar, 1997, Sejarah Jawa Barat: yuganing rajakawasa. Bandung: Geger Sunten.
| Didahului oleh: Salakanagara |
Kerajaan Hindu-Budha 358 - 669 |
Diteruskan oleh: Sunda Galuh |
Bahasa lain
Q. Kerajaan Salokanegara
R. Kerajaan Melayu
S. Kerajaan Ternate
T. Kerajaan Kutai
U. Kerajaan Champa
V. Kerajaan ...
































































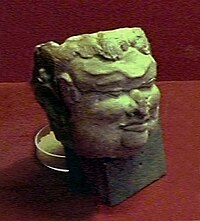









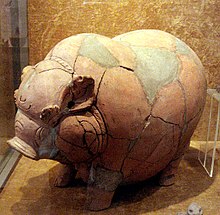







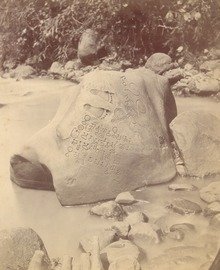








0 comments:
Post a Comment